Chapter 17 :
Unpredictable
Man
******
Violette:
AKU
duduk di sebelah
Nathan. Nathan terbaring di ruang tamu rumah Paman Locardo.
Aku gemetar. Lidahku kelu. Aku
ingin bicara, tetapi suaraku tidak keluar.
Nathan benar-benar tak sadarkan
diri sejak masuk ke mobil polisi. Aku tak tahu apa tujuan Justin sebelumnya.
Dia menyuruhku untuk masuk ke mobil polisi bersama Nathan.
Tadi, saat kami turun dari mobil
polisi, Paman dan Bibi Locardo menyambut kami dengan panik. Aku langsung
membantu para polisi untuk membaringkan Nathan di ruang tamu. Paman Locardo ternyata
sudah memanggil ambulans dan beberapa dokter. Para dokter itu mengobati Nathan
di rumah (karena jarak ke rumah sakit lebih jauh daripada ke rumah Paman
Locardo). Semuanya khawatir dan panik. Selama Nathan diobati, Bibi Locardo
memberiku minum dan menyelimutiku, mencoba untuk menenangkanku, padahal aku tak
bisa tenang sama sekali. Aku khawatir sekali pada Nathan; aku tak selera melakukan
apa pun, termasuk beristirahat.
Saat Nathan sudah selesai diobati,
para dokter dan polisi itu pun pergi. Nathan sudah bersih dan sudah berganti
pakaian. Dia juga sudah dibaringkan di salah satu kamar tamu rumah Paman
Locardo. Aku duduk di samping Nathan.
Kupandangi Nathan lekat-lekat.
Kupegang tangannya yang terasa dingin itu, lalu kucium keningnya.
Air mataku jatuh begitu saja.
Dia terlihat sangat kurus.
Rambutnya panjang. Pipinya cekung.
Apa saja yang telah menimpamu,
Paman? Apa yang mereka lakukan padamu? Apakah kau banyak merasakan sakit?
Maafkan aku…
Aku ingin Nathan bangun...dan
melihatku di sini bersamanya. Aku akan menuruti apa pun kemauannya.
"Paman...aku di sini. Cepat
sembuh, ya?" Aku menangis terisak-isak. Aku menunduk, lalu menempelkan
jemari tangan Nathan di dahiku. "I'm sorry... I'm sorry..."
Aku sangat bersyukur karena telah
menyelamatkannya. Aku ingin dia tahu bahwa aku sangat mengkhawatirkannya. Aku
juga ingin bercerita...tentang betapa sulitnya hari-hari yang kulalui tanpanya.
Aku serasa kehilangan tonggak hidupku ketika dia menghilang. Aku ingin mengadu
tentang semuanya...tentang apa yang kulakukan selama ini...tentang aku yang
menikah tanpa dia...
Semuanya...
"Paman, aku sudah menikah. Aku
minta maaf... Maaf karena kau tidak menyaksikannya saat itu…dan tidak bisa
menjadi waliku. Aku merindukanmu. Aku sudah punya suami,
Paman. You know what? Aku menikah dengan Justin, Paman. Kau pasti kaget,
‘kan?"
Aku menangis lagi. Kugenggam jemari
Nathan dengan erat. Aku takkan membiarkan siapa pun mengambilnya lagi dariku.
Tiba-tiba, pintu kamar tamu itu terbuka.
Aku melihat Bibi Locardo masuk dan menghampiriku. Dia memelukku sejenak, lalu mengusap
punggungku dengan lembut.
"Dia pasti bangun besok.
Bersabarlah..." ujar Bibi Locardo. Aku menarik napasku dan mengangguk
pelan.
"Ya...dia pasti bangun,
Bibi." Aku mengangguk dengan yakin. Aku tersenyum pada Bibi Locardo dan
dia mulai mengusap kepalaku.
"Tidurlah. Justin mungkin
sebentar lagi akan pulang," katanya. Ia lalu berjalan ke ujung ruangan
untuk mematikan sakelar. Setelah itu, dia kembali menatapku. "Kau mau
tidur di mana, Vio?"
Aku melihat sosoknya di kegelapan
dan menjawab, "Kurasa aku akan tidur di sini saja, Bibi."
Dia mengangguk. "Baiklah. Kuat-kuat,
ya. Kau harus percaya bahwa Nathan akan sembuh dan kembali beraktivitas seperti
biasa."
Bibi Locardo menghampiriku lagi dan
mencium keningku singkat.
Aku lantas mengangguk dan tersenyum
lembut padanya. Dia mengusap bahuku dengan pelan, kemudian melangkah ke pintu
kamar.
"Good night, Sweetheart," ujarnya. Dia keluar setelah mendengar
jawabanku, lalu dia menutup pintu itu.
Kamar ini kembali terasa sunyi.
Nyaris sepanjang malam, aku menatap Nathan, membenarkan selimutnya, dan berdoa untuk
kesembuhannya. Namun, pada akhirnya, aku tertidur.
******
Pagi ini, aku terbangun di samping
Nathan.
Nathan belum bangun. Aku pun
membenarkan selimutnya, lalu mengikat rambutku dan mencuci muka. Begitu keluar
dari kamar, aku pergi ke dapur dan menemukan Bibi Locardo di sana. Aku akhirnya
membantunya untuk menyiapkan sarapan.
Aku belum melihat Justin. Aku
khawatir, tetapi Paman dan Bibi Locardo berusaha untuk menenangkanku dengan
mengatakan bahwa Justin mungkin sedang ada urusan.
Masalahnya, Justin tidak cerita
‘urusan’ apa yang sedang dia selesaikan.
Setelah sarapan bersama, Paman
Locardo pun pergi bekerja. Aku bergegas mandi.
Setelah mandi, aku mendengar dari
Bibi Locardo bahwa ponselku—yang tertinggal di kamar Nathan—berbunyi. Aku
langsung berlari ke sana, berharap bahwa itu adalah Justin, tetapi setelah aku
sampai di sana, aku menatap layar ponselku dan ternyata itu bukan Justin. Itu adalah
nomor yang tak kukenal.
Aku pun mengangkat panggilan
telepon itu.
"Halo?" kataku. Dahiku
berkerut.
"Selamat pagi, Ibu. Apakah
Anda Mrs. Alexander?”
“Iya. Ada apa, ya?” jawabku. Aku
merasa aneh.
“Baik, Bu. Kami dari Bellevue
Hospital. Kami ingin memberitahukan pada Anda bahwa Mr. Alexander, Tuan Justin
Alexander, mengalami kecelakaan mobil pada dini hari ini. Kami baru saja
mendapatkan kontak kerabatnya dan langsung menghubungi Anda. Kondisi Tuan
Justin saat ini—"
Ponselku terjatuh ke lantai.
Napasku tiba-tiba sesak. Tanganku
bergetar. Jantungku serasa berhenti berdetak.
Merasa linglung, aku langsung
berlari ke luar. Bibi Locardo menanyaiku ‘ada apa’ dan aku hanya bisa menjawab
'Justin kecelakaan tadi malam.’ dengan panik. Aku hampir menangis. Bibi Locardo
terkejut bukan main; dia langsung menghubungi Paman Locardo.
Secepat kilat, mobil Paman Locardo
sudah ada di teras dan dengan panik kami semua naik mobil itu. Evan juga
terlihat pucat. Kami meninggalkan Nathan di rumah bersama para asisten
rumah tangga yang bekerja di sana.
"Paman, Bibi, nanti biar aku
saja yang menjaga Justin ketika kalian pulang ke rumah. Kumohon tolong aku,
tolong jaga Pamanku..." pintaku. Awalnya, mereka agak kaget, tetapi pada
akhirnya mereka mengangguk.
"Baiklah. Jaga Justin
baik-baik, ya,” ujar Paman Locardo dengan tegas. Dia menyetujuiku.
Aku mengangguk. “Baik, Paman.”
Setelah sampai di rumah sakit, kami
langsung menanyai resepsionis. Begitu diberitahu di mana ruangan Justin, tanpa
membuang waktu lagi, kami langsung ke sana.
Paman Locardo membuka pintu ruangan
Justin dan aroma segar dari ruangan itu langsung tercium. Aku langsung berlari dan
berdiri di samping ranjang Justin. Dia memiliki luka yang sudah diperban di
kepala dan lengannya. Dia sadar; dia melihatku datang. Agaknya,
dia sudah baik-baik saja, tetapi wajahnya tidak segar. Dia sedikit pucat.
"Apa yang terjadi, Justin?"
tanya Bibi Locardo dengan panik. Bibi Locardo menangis dan memegangi lengan
Justin. Evan memeluk dada Justin meskipun tahu tangan kecilnya takkan sampai.
Paman Locardo menghela napas.
"Kau tak pernah memikirkan dirimu sendiri saat bertindak, Justin, apa kau
sudah gila? Kalau kau mati bagaimana?!”
Justin menatap Paman Locardo dan
jakunnya terlihat naik turun.
"Lihat? Kau bahkan masih
menegakkan sifat dinginmu itu padaku di saat seperti ini! Sekarang, lihat. Kau
sedang sakit, tetapi masih juga keras kepala?!!!" teriak Paman Locardo.
Aku hanya menunduk. Nyatanya, aku
mengakui bahwa Justin memang keras kepala. Paman Locardo benar.
"I'm fine. Aku hanya tak mau menceritakannya
padamu karena kau pasti akan melarangku." Justin akhirnya menjawab,
suaranya terdengar serak.
“…Melarangmu?" tanya Paman
Locardo. Alisnya menyatu.
"Hm. Karena aku tahu kalau kau
begitu protektif,” ujar Justin. Dia memalingkan wajahnya. Satu kalimat itu
berhasil membuat Paman Locardo terdiam. Meskipun tidak gamblang, tetapi dari kata-kata
itu, semua orang bisa menyimpulkan bahwa: Justin memperhatikan Locardo.
Justin tahu sifat Locardo. Mungkin...Justin mulai melepas kebenciannya
kepada Paman Locardo sedikit demi sedikit.
Mataku membeliak ketika melihat
setitik air mata jatuh ke pipi Paman Locardo.
Paman Locardo menggeleng, lalu menghela
napas. Dia pun menarik Bibi Locardo.
"Ayo, kita serahkan ini kepada
Violette. Kita harus menjaga Mr. Morgan," ujar Paman Locardo. Bibi Locardo
lantas menatapku sejenak. Matanya lalu meneliti Justin dan ia akhirnya
mengangguk.
"Okay," katanya. Dia mulai menarik Evan.
"Kami pulang dulu, ya, Violette. Jaga Justin, oke?”
Aku mengangguk.
"Ya, Bibi. Terima kasih."
Aku tersenyum pada mereka. Mereka berdua mengangguk, lalu mulai meninggalkan
ruangan.
Aku pun menghela napas.
Kutatap Justin dengan tatapan sendu.
Dia masih diam. Aku menghampiri sebuah kursi yang ada di sudut ruangan dan
ketika aku baru saja mau menyeretnya, tiba-tiba suara dinginnya terdengar.
"Kau pucat."
Mendadak darahku serasa mendidih.
Aku langsung berbalik, kuentakkan
kakiku saat menghampiri ranjangnya. Aku memelototinya.
"KAU SENDIRI?! APA YANG KAU
LAKUKAN DI SINI? Kau seribu kali lebih pucat dariku!!! Ke mana kau pergi tadi
malam?!!! Apa kau gila, Pak Genius?!!!" teriakku. Namun, dia
hanya mengangkat sebelah alisnya.
"Jadi, begitu caramu
memperlakukan suamimu yang sedang sakit? Seharusnya kau memanjakanku,"
jawabnya enteng.
Aku menganga; aku langsung berkacak
pinggang di depannya.
"Well, fine, suamiku yang sedang sakit, sekarang
dengarkan aku!!! APA KAU TAHU SEBERAPA KHAWATIR KAMI SEMUA? CEPAT KATAKAN
PADAKU HAL GILA APA YANG KAU LAKUKAN SEMALAM!!!"
"Tenanglah, Nona," ujarnya
datar. Sialnya, pipiku sempat memerah saat mendengar panggilan itu. Namun, aku
kembali memfokuskan pendengaranku karena aku tahu dia akan menjelaskan sesuatu.
Dia menatapku dengan saksama. Parahnya,
hatiku masih sempat bergetar saat melihat matanya. Mata indahnya itu selalu
bisa menghipnotis semua orang.
"Elika ada di ruang sebelah,"
katanya.
Aku terperanjat. Justin lalu
melanjutkan, "Dia dijaga oleh beberapa polisi. Saat dia terbangun nanti,
mungkin dia akan langsung dibawa ke kantor polisi."
Aku mengangguk pelan, menunggu
lanjutan ceritanya.
Justin mulai menghela napas.
"Semalam aku mengejarnya. Aku mengambil alih kemudinya…dan kau pasti tahu
apa kelanjutannya."
Oh, aku tahu. Hal seperti ini sudah
sering dia lakukan ketika di Red Lion. Itu memang nekat bukan main. Namun, yang
dihadapinya itu adalah Elika, wanita yang sejujurnya hanya bermodalkan cinta.
Aku mengangguk. "Baik. Jadi,
kau sudah merencanakan itu sejak awal?"
Dia mengangguk.
Aku menarik napas dalam-dalam, lalu
langsung kembali memelototinya. "Jadi, sekarang kau tahu apa
kesalahanmu?!"
Dia malah mengernyitkan dahi.
Sialan.
"KAU MENCOBA UNTUK BUNUH
DIRI, SIR!!" teriakku. Matanya menyipit saat mendengar
ucapanku.
"Aku tidak bunuh diri,
Violette."
"KAU BUNUH DIRI!!"
"Tidak."
"JUSTIN!!!" teriakku
frustrasi. Akan tetapi, mataku membelalak ketika tiba-tiba tubuhku ditarik
dengan secepat kilat. Aku tak sempat melawan. Saat tersadar, aku sudah duduk
menyamping di atas pangkuan Justin; Justin menggenggam tanganku dan matanya
menatapku dalam. Dia memenjarakanku dengan tatapannya. Aku belum bisa mencerna
apa yang sedang terjadi.
"Kau selalu berisik
tiap kali aku melihatmu," bisiknya.
Aku kontan meneguk ludahku. Kulihat
ada kilat jenaka di bola mata Justin. Napasku spontan tertahan di tenggorokan.
Dia…
…tampan sekali.
Aku tak pernah menyangka bahwa
dialah yang akan menjadi suamiku. Dahulu, sempat kusangka kalau dia akan
bersama Hillda (entah bagaimana caranya), tetapi takdir berkata lain. Dia
sekarang berada di depanku, menatapku sambil tersenyum miring, dan tangannya mulai
beralih memegang pinggangku dengan lembut.
Jantungku berdebar-debar ketika dia
menyentuhku seperti itu.
Pelan-pelan, dia mendekatkan
wajahnya ke wajahku. Aku sontak menunduk dan menutup mata; kulit wajahnya yang
lembut serta napasnya yang hangat itu sudah menyentuh area wajahku.
Situasi ini membuat tubuhku jadi
sedikit gemetar. Justin meremas pinggangku…dan jempolnya mengusap pelan area
itu. Aku nyaris kehilangan akal sehatku sampai akhirnya aku mendengar suara
ketukan di pintu.
Ada beberapa suara ketukan sepatu
yang masuk ke ruangan dan aku terperanjat. Aku spontan mendorong Justin dan
menatap ke samping. Mataku membelalak saat mendapati dua perawat yang terdiam
di sana sambil melihat kami. Aku mengernyitkan dahi; aku agak heran mengapa
mereka terdiam di sana. Ada apa?
Aku refleks memandangi diriku sendiri
dan Justin…lalu aku tersadar.
Posisi kami!!
Aku melihat ke arah dua perawat itu
lagi. Mereka berdua tanpa sadar menjatuhkan catatan mereka, lalu langsung
menaruh kedua tangan mereka di pipi. Mereka mulai senyum-senyum, kesengsem
sendiri.
"Duh, mesranya..." ujar
salah satu dari mereka. Perawat yang satu lagi mengangguk cepat, menyetujui
perkataan temannya. Mereka berdua terus memandangi kami dan aku yakin kalau pipiku
telah memerah seperti kepiting rebus karena wajahku panas sekali. Rasanya
seperti sedang dibakar!!
Akan tetapi, tiba-tiba Justin
bergerak. Dia membenarkan posisi dudukku di atas tubuhnya.
Para perawat itu berteriak
histeris, mata mereka berbinar-binar saat menatap Justin melakukan itu. Aku
kontan menoleh kepada Justin.
Dahiku berkerut saat mendapati Justin
justru tersenyum pada kedua perawat itu.
"Ada apa, Suster?” tanya
Justin. Para perawat itu tersentak, lalu spontan mengambil catatan mereka yang
terjatuh. Setelah itu, sambil senyum-senyum sendiri, mereka mulai melihat
catatan mereka.
Aku mencoba untuk bangkit dari
pangkuan Justin, tetapi tangan Justin langsung mencengkeram pinggangku
kalau aku bergerak sedikit saja.
Aku pun akhirnya menyerah dan hanya
bisa menunduk. Aduh, aku malu sekali! Kami sedang berada di rumah sakit, bukan
di rumah kami sendiri!!
Salah satu dari perawat itu lalu
berkata, "Umm... Mr. Alexander sudah diperbolehkan pulang hari ini. Dokter
akan berkunjung sebentar lagi untuk memastikan kondisi Mr. Alexander."
Justin mengangguk.
Aku langsung menghela napas lega.
Syukurlah, Tuhan.
Kedua perawat itu lalu pamit dan keluar
ruangan sambil senyum-senyum. Mereka salah tingkah dan mulai menyikut satu sama
lain. Aku mendengar mereka berbisik, 'Tampan sekali!' saat
mereka ke luar.
Yah, semua orang yang matanya normal
pasti akan bilang begitu. Soalnya, pria yang ada di dekatku ini memang gantengnya
tidak masuk akal.
Aku mengedikkan bahu. Namun,
tiba-tiba aku teringat sesuatu.
Posisi kami!!
Mataku memelotot; aku langsung
menghadap ke arah Justin. "Aku mau turun! Apa yang kau lakukan?!!"
"Hmm…? Kupikir kau betah duduk
di pangkuanku," ujar Justin sembari tersenyum miring. Mataku membulat.
"Aku mau turun!!"
teriakku. Aku memberontak, tetapi dia menarikku kembali.
"Apa sebaiknya kita lanjutkan saja
yang tadi?" ujarnya lirih.
Aku yakin aku benar-benar menganga.
Aku kembali berteriak kencang. Sayangnya, ini adalah ruang VIP yang kedap
suara.
Siaaaal!
******
Kami sudah sampai di rumah Paman
Locardo.
Aku ingin mengemudi, tetapi Justin bilang
dia bisa melakukannya. Dengan menyebalkannya, dia bilang dia tidak sakit. Hanya
memar sedikit, katanya. Aku jadi tak punya pilihan lain selain melihatnya
dari samping. Aku jadi selalu khawatir padanya dan aku jadi curiga. Apakah aku
sekarang jadi tergila-gila padanya? Atau…apakah aku terlalu mencintainya? Demi Neptunus,
aku tak mengerti. Namun, di sisi lain, tiap kali berhadapan dengannya, aku bisa
emosi tingkat dewa.
Saat kami baru masuk ke rumah dan melewati
ruang tamu yang superlebar itu, suara Paman Locardo menghentikan langkah kami.
Paman Locardo menatap Justin dengan tajam.
"Aku sudah mendengar tentang
Red Lion dari Mr. Morgan saat dia sadar tadi. Kau benar-benar tak menceritakan
apa pun padaku soal Red Lion."
Mataku membeliak. Sementara itu, Justin
mengernyitkan dahinya.
Kulihat Justin mulai berjalan pelan
menghampiri Paman Locardo yang sedang duduk di sofa ruang tamu dan aku pun kontan
mengikutinya. Ternyata, Nathan sudah bangun. Dia duduk di seberang Paman
Locardo. Melihat itu, aku langsung berlari menghampirinya.
Aku duduk di samping Nathan. Air
mataku jatuh begitu saja. Nathan pun menatapku dengan lembut, tubuhnya agak
bergetar karena dia mulai menangis.
Nathan mengelus pipiku dengan
tangan kurusnya. Aku menangis kencang dan langsung memeluknya.
Nathan membalas pelukanku, lalu mengusap
bagian belakang kepalaku.
"Violette..." bisiknya di
sela tangisnya. "Kau baik-baik saja, hm?"
Air mataku jatuh semakin deras.
"Aku baik-baik saja, Paman...
Aku baik-baik saja…" bisikku, bibirku bergetar.
Nathan mengecup kepalaku singkat. "Kau
sudah menikah, hmm? Selamat, ya... Selamat. Aku menyayangimu..."
Aku mengangguk. Aku tak mampu berbicara
apa pun lagi. Hanya bisa berterima kasih pada Tuhan dalam hati karena telah mempertemukanku
lagi dengan Pamanku.
Ketika pelukan kami terlepas, aku
mengusap air mataku dan menatap Nathan dengan penuh haru. Kulihat
pandangan Nathan mulai beralih pada Justin yang duduk di sisi kanannya—aku duduk
di sisi kirinya—dan tatapannya begitu lembut.
Mereka saling memeluk. Nathan mengusap
punggung Justin…dan Justin juga melakukan hal yang sama.
"Ternyata, apa yang ada di
dalam pikiranku itu benar..." Nathan berbisik. "Kalian benar-benar ditakdirkan
untuk bersama. Jaga Violette untukku, Justin."
Justin tersenyum. Setelah itu,
Nathan pun melanjutkan, "Violette ini keras kepala. Dia juga cerewet,
tetapi aku ingin kau menjaganya..." ujar Nathan. Aku tertawa renyah meski
aku tahu kalau dia sedang menghinaku.
Justin tertawa pelan. "Aku
tahu, Paman. Aku akan menjaga Violette dengan baik."
Ada jenaka yang terkandung di suara
Justin. Setelah mengatakan itu, Justin tertawa bersama Nathan. Mereka lalu
berpelukan. Setelah pelukan mereka terlepas, Justin langsung menoleh kepada Paman
Locardo.
Justin menatap Locardo dengan
sungguh-sungguh. Pria itu lalu berkata, "Tentang Red Lion...maafkan
aku."
Paman Locardo menunduk. Pria itu menghela
napas, lalu mengangguk.
"Sekarang jelaskan padaku. Aku
memang sudah dengar soal itu dari Mr. Morgan, termasuk tentang Violette yang
juga berasal dari organisasi yang sama. Namun, aku ingin mendengarnya dari
mulutmu langsung,” ujar Paman Locardo dengan tegas.
Mataku melebar.
Aku melihat Justin yang mulai
sedikit menunduk. Dia bernapas samar, lalu menjawab.
"Kau tahu kalau orangtuaku meninggal
karena kecelakaan. ‘kan? Mereka sudah tinggal di Perancis selama setahun lebih,
tetapi tiba-tiba truk Ayah yang membawa kami saat itu kecelakaan. Aku tak kenal
siapa-siapa di sana karena semua keluarga yang kutahu hanya ada di New York.
Itu pun, aku tak pernah bertemu dengan mereka. Keluargaku belum pernah
membawaku ke New York. Aku kehilangan kedua orangtuaku dan aku tak tahu harus
menghubungi siapa. Keluarga kami saat itu benar-benar miskin. Truk itulah
satu-satunya yang barang berharga kami. Anak kecil yang selamat dari kecelakaan
besar… Bukankah aku beruntung?” Justin memberi jeda sejenak.
“Brian adalah Ketua Red Lion yang
kebetulan menyelamatkanku. Dia merawatku bersama anak-anak lainnya, lalu
mengajak kami untuk bergabung di organisasi yang dia buat, yakni Red Lion. Pada
dasarnya, Red Lion hanyalah sekumpulan pencuri, tetapi Brian melakukan banyak
hal agar kekuatan kami besar. Red Lion sudah dianggap seperti teroris. Violette
adalah satu-satunya anggota perempuan di Red Lion dan dia akhirnya ditugaskan
untuk menjadi rekanku. Brian menunjukku untuk menjadi tangan kanannya.
Akan tetapi, tiba-tiba saja…aku
terlibat cinta. Aku terlibat hubungan terlarang," Justin menggeleng,
dahinya berkerut saat mengingat itu. "Parahnya, wanita itu adalah
Hillda, istri dari seorang pengusaha terkenal di Perancis yang bernama
Martinous Hoult. Akibat perselingkuhan istrinya denganku, dia pun mengincarku.
Untuk mengincarku, dia pasti akan mengincar Red Lion terlebih dahulu.
Aku tak mau Red Lion mati di tangan
mereka. Daripada semua itu terjadi, lebih baik kuakhiri Red Lion. Lagi pula, Red
Lion adalah organisasi yang tidak benar. Aku pun mengakhiri organisasi itu
bersama Violette karena Violette adalah orang yang paling kupercaya. Kami
sudah lama berteman dan…kami memang paling dekat dengan satu sama lain. Tidak
ada lagi peperangan, tidak ada lagi teroris, semuanya tertutupi seolah-olah
kami semua mati dibom. Aku memanipulasi segalanya. Jadi, semua tentang Red Lion
betul-betul hilang ditelan bumi dan aku menyelamatkan diriku bersama Violette.
Meskipun sulit, akhirnya kami
berbaikan dengan Martinous Hoult. Aku memutuskan hubunganku dengan Hillda, lalu
pergi ke New York bersama Violette. Seluruh media memberitahukan bahwa Red Lion
telah musnah, jadi semua orang akan berpikir seperti itu. Setidaknya takkan ada
yang mencari ataupun mencurigai kami. Lagi pula, wajah kami memang tak terlalu
dikenali oleh polisi saat di Red Lion karena kami selalu berhati-hati.
Setelah itu, aku pun bertemu
denganmu," kata Justin. Ia menatap Locardo dan Locardo mengangguk. Ia pun
melanjutkan, "Selama dua tahun lebih, aku tak pernah bertemu dengan
Violette lagi. Namun, tiba-tiba, aku berjumpa dengannya yang sudah bekerja di
perusahaanku. Ternyata, dia juga tinggal dengan pamannya. Aku menjadikannya executive
assistant-ku, lalu tiba-tiba pamannya diculik. Pelakunya adalah seorang
manager yang pernah jadi rekan seks-ku saat aku baru tinggal bersamamu.
Saat itu…aku masih tidak stabil, ‘kan?”
Locardo kembali mengangguk,
mengiyakan Justin.
Justin lantas melanjutkan, “Namanya
adalah Elika. Elika tahu tentang Red Lion. Ternyata, dia menemukan salah satu
anak buah Martin yang diperintah untuk menyerangku di pertempuran itu. Waktu
itu, aku mengebom mereka semua, tetapi ternyata ada yang lolos. Dialah orangnya.
Dia bernama Welton. Welton dendam pada Red Lion karena telah mengambil
teman-temannya dan menghancurkan hidupnya.
Karena Elika ingin menjauhkan
Violette dariku, dia pun berkata pada Welton bahwa masih ada satu anggota Red
Lion yang tersisa, yaitu Violette. Mereka lantas bekerja sama dan menyekap
Nathan. Semalam, aku berhasil menangkap Welton, dan akhirnya Welton tahu bahwa
Red Lion yang tersisa bukan hanya Violette. Justru akulah pelaku yang
dia cari.”
“Apa sekarang dia sudah dibawa oleh
polisi?” tanya Paman Locardo.
“Hm.” Justin mengangguk. “Selain
itu, tadi malam…aku tidak pulang karena mengejar Elika. Aku tahu kalau dia
pasti akan melaporkan keberadaan Red Lion di New York. Namun, aku berhasil
membungkamnya dengan kecelakaan itu. Sekarang, kita harus menunggu apakah dia
akan meninggal di rumah sakit atau berhasil hidup dan
dipenjara. Dia tadi ada di rumah sakit yang sama denganku."
Justin bercerita sebanyak itu
dan kami semua mendengarkan dengan saksama. Ada sedikit—sangat sedikit—hal yang
tak kutahu dan sekarang aku jadi mengetahuinya.
Paman Locardo mengembuskan napasnya
kuat, lalu menggeleng. Dia pun menatap Justin dengan intens.
Auranya terasa begitu menekan
ketika ia berbicara dengan tegas. Ia mulai mengancam Justin. "Jangan
ulangi apa yang semalam kau lakukan. Mulai sekarang, karena aku sudah tahu
semuanya, kalian akan kujaga dengan lebih ketat. Jangan membuatku khawatir
lagi. Akan kuperintahkan banyak orang untuk menjaga lingkungan rumah kalian.
Tutupi semua tentang Red Lion dengan baik. Lupakanlah masa lalu kalian itu."
Sejak Justin menjadi pemimpin
Alexander Enterprises Holdings, Inc., Paman Locardo membeli perusahaan lain.
Aku hanya menunduk karena tak bisa
mengatakan apa pun. Paman Locardo berhak melakukan semua itu setelah kekacauan
ini. Dia juga hanyalah seorang paman yang khawatir pada keponakannya.
"Aku bisa melakukannya sendiri.
Aku lebih tahu apa yang harus kulakukan, Paman," jawab
Justin dengan tenang.
Sebentar.
‘Paman’?!!
Justin memanggil Paman Locardo
dengan sebutan ‘Paman’?!!!!
Mata kami semua membelalak. Oh,
Tuhan, akhirnya!!!!
Aku tersenyum penuh haru; aku hampir
menangis. Akhirnya, otak Justin sedikit lebih waras. Aku senang sekali melihat
perkembangan hubungan mereka.
******
Aku masuk ke kamar. Hari ini,
Justin memutuskan untuk menginap di rumah Paman Locardo. Lagi pula, Paman dan
Bibi Locardo memang memaksa kami untuk tinggal, apalagi Nathan juga ada di
sini. Paman dan Bibi Locardo menyiapkan satu kamar khusus untukku dan Justin.
Aku masuk ke kamar karena ingin
melihat ponselku. Ponselku berbunyi, pertanda ada sebuah pesan yang masuk. Ketika
kulihat layar ponselku, ternyata itu cuma pesan dari operator. Aku menganga dan
kontan mendengkus kesal. Apa-apaan! Aku tadi berlari dari dapur hanya karena
pesan itu, padahal aku sedang membantu Bibi memasak makan malam.
"Sedang apa?"
Mataku melebar. Aku kenal suara
itu.
Aku mulai berbalik dan melihat
Justin yang sudah bersandar di kosen pintu; dia memandangiku dengan lekat. Aku
mengedipkan mataku dua kali—agak kaget karena aku sama sekali tak mendengar langkah
kakinya—lalu menjilat bibirku. "Oh. Tadi ada pesan."
Justin berdiri tegap, lalu berjalan
ke arahku. Pandangan matanya masih tidak berubah. Melihatnya berjalan ke arahku
dengan tatapan seperti itu…membuatku tanpa sadar meneguk ludah. Aku merasa
begitu terintimidasi, ciut, seperti tikus yang sedang didekati
pelan-pelan oleh kucing.
Setahuku, tadi dia sedang bersama
Paman Locardo. Mengapa tiba-tiba dia ada di sini?
"Pesan dari siapa?"
tanyanya dengan suara dingin. Aku tersentak.
Entah mengapa, aku jadi gugup. Akan
tetapi, aku berusaha untuk menormalkan ekspresiku, soalnya aku tahu bahwa
Justin tidak sedang marah padaku.
"Dari operator. Aku sudah
susah payah ke sini," keluhku. Aku mengedikkan bahu.
Dia berhenti tepat di hadapanku.
Tatapannya seolah-olah bisa menembus jiwaku.
Aku harus mengalihkan perhatiannya.
"Justin, kau mau kopi? Aku sedang membantu Bi—"
"Aku tidak mau
kopi,” potongnya dengan cepat dan singkat. Nadanya datar.
Aku memiringkan kepalaku.
"Jadi, kau mau apa? Sesuatu yang lain?"
"Hm," dehamnya. Dia menyilangkan
tangannya di dada, lalu berkata, "Aku ingin sesuatu yang hanya kau
yang bisa mengabulkannya."
Aku menyatukan alis. Hanya aku?
"Maksudmu apa, sih? Jangan
berbelit-belit!" kataku. Aku jadi pusing kalau disuruh menebak begitu.
Namun, tak memedulikan
pertanyaanku, dia malah berjalan melewatiku. Aku spontan menganga, lalu
berbalik. "Hei!! Kau mau apa, sih?! Justin!!"
Dia berjalan ke arah jendela kamar
yang gordennya terbuka, lalu berdiri membelakangiku di sana.
Tubuh tegapnya sungguh sempurna meskipun
hanya kulihat dari belakang. Bentuk tubuhnya tercetak sempurna di body fit
t-shirt-nya yang berwarna hitam. Dia memakai celana chino panjang
berwarna krem.
Dia tampak sangat memesona meskipun
hanya memakai pakaian biasa. Dia membuat pakaian yang biasa jadi tampak luar
biasa.
Aku terdiam. Sibuk mengagumi
sosoknya yang membelakangiku. Akan tetapi, aku ingat bahwa Justin belum
menjawab pertanyaanku.
"Justin?" panggilku.
Tak kusangka, dia mulai menoleh ke
belakang.
"Hm," dehamnya.
Sungguh, mataku melebar saat melihat
betapa bersinarnya wajahnya saat ini. Sinar matahari sore yang masuk melalui
jendela itu membuatnya terlihat semakin memesona.
Dengan gugup, aku pun mencoba untuk
berbicara, "K—Katakan padaku kau ingin minum apa. Umm…atau kau tak ingin
minum?"
Justin menghela napas. Akhirnya,
dia pun berbalik. Kulihat tangannya ada di saku celananya; dengan santai, ia
melangkah mendekatiku. Aroma tubuhnya yang maskulin itu tercium semakin jelas. Jantungku
berdegup kencang saat dia semakin dekat denganku. Aku otomatis menunduk ketika sadar
bahwa dia tengah menatapku dalam sembari mendekatiku. Tubuhku bisa
bergetar jika aku terus menatapnya.
Lama aku terdiam…dan kukira dia
hanya berdiri di depanku. Namun, aku salah.
Saat aku baru mau menatap wajahnya,
tiba-tiba…dia memelukku dengan lembut. Dia melingkarkan sebelah tangannya pada
pinggangku dan sebelah tangannya lagi mulai menyentuh daguku.
Di tangan kirinya, dia memakai
sebuah jam tangan berwarna hitam. Tangan itulah yang ia gunakan untuk menyentuh
daguku. Pipiku memerah tatkala dia mulai mengangkat wajahku. Matanya serasa berkabut.
Apa yang sedang ia lakukan? Aku gugup
sekali, nih! Sejak tadi, aku hanya mendengar suara detak jantungku saja, tak
mendengar apa-apa lagi.
Apakah jantung Justin juga berdegup
kencang sepertiku? Rasanya dia tenang-tenang saja...
Jempolnya mengusap daguku, lalu dia
mengembuskan napasnya samar.
"Apa kau sudah lupa dengan malam
pertama, Nona?" tanyanya lirih.
Mataku spontan membulat. Pipiku
merona. Kurasa, degup jantungku semakin menggila. Astaga...aku…
…aku belum siap. Aku belum siap
untuk itu. Demi Tuhan, aku belum siap.
"Jawab aku," ujarnya dingin. Tegas. Aku
semakin kaget. Dia biasanya tak mempermasalahkan itu, tetapi mengapa hari ini
tiba-tiba dia...
"Aku… Aku belum siap, Justin..."
Aku mengaku. Kupejamkan mataku. Aku pasti terdengar begitu aneh karena tidak siap
melaksanakan kewajibanku sebagai seorang istri.
Ketika dia bahkan menginginkannya
seperti ini…
Seharusnya aku bersyukur karena dia
memiliki ketertarikan seksual padaku, padahal selama ini kukira dia tak tertarik.
Soalnya, dia memang tak pernah mempermasalahkan hal ini.
Justin hanya diam, tetapi aku tahu
kalau matanya masih mengawasiku. Aku menggigit bibirku. Apa ia marah?
Namun, aku salah lagi.
Nyatanya, Justin mulai mendekatkan
wajahnya ke wajahku. Karena aku sedang menunduk, dia pun jadi ikut menunduk
demi mencari wajahku.
"Aku tak yakin kalau
aku bisa menunggu lebih lama dari ini, Mrs. Alexander," bisiknya.
Pipiku merona. Aku malu sekali. Ya Tuhan, tolong jauhkan makhluk yang nyaris
sempurna ini dariku…
Aku terlalu malu untuk mengangkat
wajahku, tetapi dia tetap menempelkan wajahnya dengan wajahku. Setelah itu, aku
merasa ada sesuatu yang lembut dan basah mulai mengecup bibirku. Aku spontan melebarkan
mata, tetapi tiba-tiba dia semakin merapat. Tubuhnya yang kekar itu mulai
memelukku. Sebelah tangannya bersandar di pinggangku, sementara sebelahnya lagi
memegang bagian belakang kepalaku. Pelukannya terasa begitu hangat dan nyaman,
membuatku merasa dilindungi.
Bibirnya melumat bibirku; dia tidak
menciumku dengan liar. Ciumannya sangat lembut. Tangannya kini menjalar hingga
ke bagian belakang pinggulku; dia mengalungkan tangannya di sana dan menarikku agar
lebih mendekat.
Aku mencoba menggerakkan tanganku,
lalu kupegang lengan Justin yang sedang memelukku. Mengenggamnya takut-takut
ketika Justin memperdalam ciumannya.
"Uncle Jus—tin? Sedang apa…?"
Aku spontan membuka mata; kujauhkan
bibir Justin yang menempel di bibirku.
Justin sedikit mengernyitkan
dahinya, sementara aku langsung menoleh ke belakang tanpa memedulikan Justin. Namun,
tangan Justin masih melingkar di tubuhku.
Mataku membelalak ketika melihat
ada Evan berdiri di pintu kamar; dia menganga melihat kami berdua. Kini,
agaknya Justin sudah sadar kalau aku tengah melihat sesuatu, jadi Justin
mulai melepaskan pelukannya pelan-pelan.
Aku meneguk ludah.
"Ada apa, Roger?" tanya
Justin. Cara bicaranya seperti anak-anak; dia biasa berbicara dengan baby
talk kepada Evan. Justin menyentuh punggungku sebentar—mengisyaratkan bahwa
dia akan menghampiri Evan—lalu dia pun mendekati Evan. Karena agak shock,
tubuhku pun terus mematung. Aku menganga.
Sebentar…
Evan—Evan melihat kami!!!!
Bagaimana ini?! Ini bisa memberikan dampak yang buruk bagi Evan nantinya!
"Uncle sedang apa? Tadi, Mama panggil Kak
Vio. Mama minta tolong Kak Vio buat potong daging," kata Evan. Dia cemberut;
disilangkannya tangannya di depan dada, pertanda bahwa dia marah pada kami. Um...atau
mungkin…hanya padaku. Kulihat Justin mulai berjongkok di depannya.
"Kak Violette memeluk Uncle sangat
erat tadi." Justin menjawab Evan sambil tersenyum miring. Mataku membulat.
Justin pun melanjutkan, "Kak Violette tak mau ditinggal."
Sial, apa maksudnya itu?! Aku
tak pernah bilang begitu!
"Justin!!" teriakku tak
terima, tetapi Justin tak menghiraukanku. Dia malah menggendong Evan dan mereka
berdua kini menghadap ke arahku.
Evan tersenyum jail padaku. "Hayoooo...
Kak Violette tadi mau ngapa-ngapain, yaa, sama Uncle Justin? Jangan-jangan...
Uhuk-uhuk..."
Astaga, dari mana dia mempelajari
semua itu? Evan, ya ampun! Siapa yang mengajarkannya?!
Aku berteriak, "Evan! Bukan
begi—"
Evan tertawa geli. Dia terus
mengejekku hingga Justin tertawa karenanya.
Karena malu sekaligus kesal, aku
pun berlari ke luar. Dengan cepat, aku pergi ke dapur, lalu langsung membantu
Bibi Locardo. Aku berpura-pura seolah-olah tak terjadi apa-apa, tetapi agaknya Bibi
Locardo tertawa kecil saat melihatku.
Apakah suara Evan tadi kedengaran
sampai ke dapur? Oh, Tuhan!!! Aku malu sekali!! []








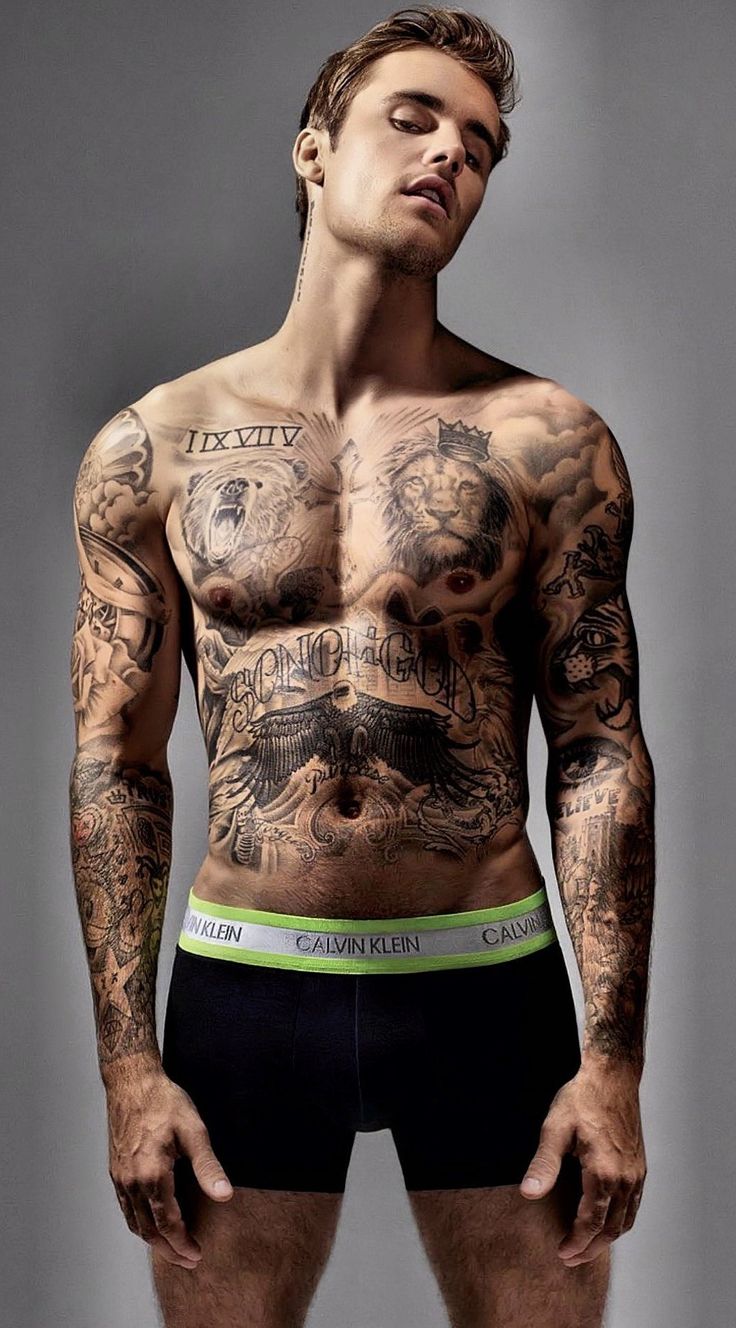





No comments:
Post a Comment